SEORANG perempuan menatap cermin. Lama. Kadang pinggulnya dihadapkan, lalu yang sebelahnya. Wajahnya didekatkan, lalu diusap-usap. Rambut, bulu mata, gincu, hidung, pakaiannya diperiksa teliti. Ia merasa masih ada yang kurang. Bisiknya, “Aku harus ke salon lagi!”
Usianya masih tergolong abege. Ia merasa tidak pede. Entah untuk apa dan pada siapa. Yang jelas, ia ingin teman-teman, terutama yang pria memperhatikan penampilannya. Ia ingin mereka memberi komentar sempurna, lalu takluk di kerlingnya. Setiap kali ia merasa cantik, ada saja yang kelihatan lebih cantik. Komentar teman prianya pun tak seperti yang ia harapkan, kecuali yang sudah berumur.
Uang yang diinvestasikan untuk mempercantik diri sudah tak terhitung. Tapi tak ada pula pria yang tertarik. Hasrat ingin dibelai makin menghujam di hati dan pikirannya. Ketika hasrat itu datang, sekujur tubuhnya bergetar, seperti harimau yang hendak menerkam mangsanya. Siapa saja.
Ada banyak orang seperti itu di negeri ini. Bahkan negeri ini pun demikian. Bolak-balik membenahi diri, tetap saja tidak pede. Gonta-ganti salon, bahkan mengorbankan bagian tubuh yang lain. “Sudah bagus. Penampilanmu kini sudah oke, tapi, maaf, negeri tetanggamu ternyata jauh lebih bagus.” Seorang dari negeri seberang, yang memiliki banyak duit, ketika tiba di sini, menambahkan, “luar biasa! Ternyata yang dia maksud adalah “kalau dilihat dari luar, biasa saja.”
Anak negeri sendiri yang berminat membelainya, seolah mencemooh dengan mengatakan, “apa yang bisa diharapkan dari aturan tenaga kerja yang tidak fleksibel. UU Pajak, UU Investasi, birokrasi, pungli, korupsi, dan kepastian hukum, keamanan, dan macam-macam masalah HAM atau teroris.”
Permak lagi. Adakan diskusi, undang tokoh dari luar. Lalu, para petinggi negeri ini meributkan penghasilan, mirip ‘jablai’ yang memperbisikkan penghasilan dari si hidung belang. Jangankan mau peduli pada demo yang memprotes, atau pekerja yang terkena PHK. Lupa!
Sebuah survei, layaknya kontes kecantikan kelas dunia, digelar. Ternyata benar! Peringkat daya saingnya naik, demikian survei Internasional Finance Corporation dan World Economic Forum. Tapi, maaf, kenaikan yang dicapai negara lain jauh lebih tinggi. “Sedikit lagi. Dan, lebih cepat lagi. Kau harus memperbaiki ini, itu, dan inu! Percayalah, kau memiliki potensi luar biasa. Pada 2025, kau akan jadi primadona. Pada 2050, kau akan mengalahkan negara-negara yang sekarang disebut maju!”
Berkaca lagi, ke salon lagi. Senyum-senyum sendiri. Ada kebanggaan dengan dongeng-dongeng dan pujian itu. Berlenggak-lenggok lagi, menjajakan diri di tempat sendiri, mengharap ada yang datang menawar. Meski cuma datang, lalu pergi lagi. Sedikit yang menanamkan modalnya. Barangkali perlu langsung mendatangi pemodal di negerinya. Duta diutus, cuap-cuap akan kemolekan negerinya. Minyaknya wangi, hutannya rimbun, mulus. Semua gampang diatur. “Pokoknya, dijamin enak deh!”
Keluhan orang-orang asing didengarkan, tapi keluhan riil pengusaha lokal seperti angin lalu. Dengarlah keluhan yang disampaikan Siswono Yudhohusodo, pengusaha yang pernah menjadi calon wakil presiden dalam forum Indonesian Economic and Financial Platform Toward 2025. “Kalau saya membawa seekor sapi dari Sumbawa ke Jakarta, ongkosnya 165% lebih mahal daripada mendatangkan sapi dari Darwin, Australia. Juga, biaya angkut barang dari Batam ke Jakarta mencapai Rp 10 juta per kontainer. Padahal biaya angkut dari San Fransisco ke Jakarta cuma Rp 6 juta.”
Itu adalah persoalan sesungguhnya dari bangsa ini. Tapi apa daya. Begitu hebatnya hasrat ingin dibelai. Hasrat itu makin membuncah, mencacah batas-batas norma. Ya, seperti abege yang jarang dibelai (jablai) itu. n rizagana
Tulisan ini telah dimuat di Investor Daily edisi Selasa, 26 September 2006 halaman 24
Rubrik RASAN.
Monday, September 25, 2006
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
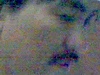
No comments:
Post a Comment