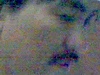SEORANG perempuan menatap cermin. Lama. Kadang pinggulnya dihadapkan, lalu yang sebelahnya. Wajahnya didekatkan, lalu diusap-usap. Rambut, bulu mata, gincu, hidung, pakaiannya diperiksa teliti. Ia merasa masih ada yang kurang. Bisiknya, “Aku harus ke salon lagi!”
Usianya masih tergolong abege. Ia merasa tidak pede. Entah untuk apa dan pada siapa. Yang jelas, ia ingin teman-teman, terutama yang pria memperhatikan penampilannya. Ia ingin mereka memberi komentar sempurna, lalu takluk di kerlingnya. Setiap kali ia merasa cantik, ada saja yang kelihatan lebih cantik. Komentar teman prianya pun tak seperti yang ia harapkan, kecuali yang sudah berumur.
Uang yang diinvestasikan untuk mempercantik diri sudah tak terhitung. Tapi tak ada pula pria yang tertarik. Hasrat ingin dibelai makin menghujam di hati dan pikirannya. Ketika hasrat itu datang, sekujur tubuhnya bergetar, seperti harimau yang hendak menerkam mangsanya. Siapa saja.
Ada banyak orang seperti itu di negeri ini. Bahkan negeri ini pun demikian. Bolak-balik membenahi diri, tetap saja tidak pede. Gonta-ganti salon, bahkan mengorbankan bagian tubuh yang lain. “Sudah bagus. Penampilanmu kini sudah oke, tapi, maaf, negeri tetanggamu ternyata jauh lebih bagus.” Seorang dari negeri seberang, yang memiliki banyak duit, ketika tiba di sini, menambahkan, “luar biasa! Ternyata yang dia maksud adalah “kalau dilihat dari luar, biasa saja.”
Anak negeri sendiri yang berminat membelainya, seolah mencemooh dengan mengatakan, “apa yang bisa diharapkan dari aturan tenaga kerja yang tidak fleksibel. UU Pajak, UU Investasi, birokrasi, pungli, korupsi, dan kepastian hukum, keamanan, dan macam-macam masalah HAM atau teroris.”
Permak lagi. Adakan diskusi, undang tokoh dari luar. Lalu, para petinggi negeri ini meributkan penghasilan, mirip ‘jablai’ yang memperbisikkan penghasilan dari si hidung belang. Jangankan mau peduli pada demo yang memprotes, atau pekerja yang terkena PHK. Lupa!
Sebuah survei, layaknya kontes kecantikan kelas dunia, digelar. Ternyata benar! Peringkat daya saingnya naik, demikian survei Internasional Finance Corporation dan World Economic Forum. Tapi, maaf, kenaikan yang dicapai negara lain jauh lebih tinggi. “Sedikit lagi. Dan, lebih cepat lagi. Kau harus memperbaiki ini, itu, dan inu! Percayalah, kau memiliki potensi luar biasa. Pada 2025, kau akan jadi primadona. Pada 2050, kau akan mengalahkan negara-negara yang sekarang disebut maju!”
Berkaca lagi, ke salon lagi. Senyum-senyum sendiri. Ada kebanggaan dengan dongeng-dongeng dan pujian itu. Berlenggak-lenggok lagi, menjajakan diri di tempat sendiri, mengharap ada yang datang menawar. Meski cuma datang, lalu pergi lagi. Sedikit yang menanamkan modalnya. Barangkali perlu langsung mendatangi pemodal di negerinya. Duta diutus, cuap-cuap akan kemolekan negerinya. Minyaknya wangi, hutannya rimbun, mulus. Semua gampang diatur. “Pokoknya, dijamin enak deh!”
Keluhan orang-orang asing didengarkan, tapi keluhan riil pengusaha lokal seperti angin lalu. Dengarlah keluhan yang disampaikan Siswono Yudhohusodo, pengusaha yang pernah menjadi calon wakil presiden dalam forum Indonesian Economic and Financial Platform Toward 2025. “Kalau saya membawa seekor sapi dari Sumbawa ke Jakarta, ongkosnya 165% lebih mahal daripada mendatangkan sapi dari Darwin, Australia. Juga, biaya angkut barang dari Batam ke Jakarta mencapai Rp 10 juta per kontainer. Padahal biaya angkut dari San Fransisco ke Jakarta cuma Rp 6 juta.”
Itu adalah persoalan sesungguhnya dari bangsa ini. Tapi apa daya. Begitu hebatnya hasrat ingin dibelai. Hasrat itu makin membuncah, mencacah batas-batas norma. Ya, seperti abege yang jarang dibelai (jablai) itu. n rizagana
Tulisan ini telah dimuat di Investor Daily edisi Selasa, 26 September 2006 halaman 24
Rubrik RASAN.
Monday, September 25, 2006
Tuesday, September 19, 2006
Kembang Uang
“MENJADI kaya itu mulia.” Kata-kata itu bergaung ke seluruh dataran Cina. Deng Xiao Ping menggunakan kalimat itu untuk menggantikan slogan yang sebelumnya dikumandangkan Mao Zhedong dari ajaran Marxis, “sama rata, sama rasa.” Sejak itu, negeri Tirai Bambu itu memangkas habis semua rumpun bambu dan menggantikannya dengan jalan mulus bebas hambatan, pabrik-pabrik, apartemen, perumahan, dan gedung-gedung perkantoran. Miliaran rakyat (negara) Cina berlomba-lomba mengejar kekayaan. Juga kemuliaan?
“Menjadi kaya itu mulia.” Demikian pastor, pendeta dan guru-guru ngaji berkotbah di mana-mana. Mereka mencontohkan Nabi Sulaeman, yang kaya raya. Banyak pula orang yang mengingikuti. Dengan kekayaannya, mereka ikhlas bersedekah, menolong anak yatim dan orang miskin-papa, membangun rumah ibadah, beribadah, dan beramal yang lainnya.
“Menjadi kaya itu mulia.” Banyak orang, dulu dan sekarang, berkata begitu. Mereka pun berlomba-lomba mencari kekayaan dengan cara-cara mulia atau tidak mulia. Dengan kekayaan, ia bisa meraih ketenaran. Masuk koran, majalah, tv, apalagi tercatat sebagai orang terkaya sejagad. Dengan kekayaan itu juga ia bisa membangun rumah mewah, menyekolahkan anak di sekolah mahal, bahkan di luar negeri, membeli mobil-mobil mewah, membeli ijazah lewat jalan pintas, hingga meraih kekuasaan.
Qorun di jaman Nabi Musa --keduanya masih sepupu(?)--barangkali, berkata begitu juga. “Menjadi kaya itu mulia.” Bahkan ia tidak menerima kemuliaan anak pamannya itu sebelum akhirnya ditelan bumi. Sekarang, setiap orang yang mendapat harta tak bertuan dari dalam bumi disebut harta karun. Atau Robin Hood. Hikayat dari Inggris yang terkenal di seluruh jagad ini, bisa jadi menganggap, “menjadi kaya itu mulia.” Sehingga ia silap mata, dan rela menjadi tumbal peradaban. Ia ingin orang-orang miskin bisa jadi kaya, menikmati ‘kemuliaan’ seperti orang-orang kaya.
Rasanya, tak ada yang menyangsikan “menjadi kaya itu mulia.” Oleh karena itu, banyak orang yang mengejar dan meraihnya dengan cara apa dan bagaimana pun. Mulia atau tidak. Dan, banyak orang membelanjakannya dengan cara apa pun pula. Mulia atau tidak. Untuk kenyamanan, keamanan, kehormatan, dan ketenaran. Untuk bergaul dengan orang kaya, sekaligus ‘menggauli’ dan ‘memperkosa’ orang-orang miskin, atau yang tak sekaya ia.
“Menjadi kaya itu mulia.” Tapi tak sedikit pula yang mengatakan, “menjadi miskin itu mulia.” Lalu kata-kata itu dibolak-balik. Bingung dan membingungkan. Antara kemuliaan di kehidupan ini dan setelah ini. Antara kemuliaan dan kehinaan. Antara siapa yang kaya, dan siapa yang miskin. Seperti apa yang terjadi belakangan ini.
Ketika jutaan orang berjuang dalam kemiskinan, mengumpulkan uang recehan, uang logam cepe’-an, di jalan-jalan, di pasar-pasar tradisional, di sekolah-sekolah, di pelosok-pelosok untuk menyambung hidup. Ketika jutaan orang habis-habisan dihantam gempa, disapu badai tsunami, ditimpa tanah longsor, diusir lumpur panas. Ketika negeri ini berteriak miskin, lalu membagi beban kemiskinan itu kepada 220 juta rakyat dalam bentuk kenaikan harga BBM dan harga-harga lain, minta-minta orang asing datang dan berinvestasi, mengutang ke sana kemari. Ketika jutaan rakyat berebut jatah bulanan sebesar Rp 100.000 dari pemerintah sebagai kompensasi BBM.
Dan, ketika ada sebuah pesta pernikahan yang membagikan kembang uang kertas senilai Rp 70.000 dan dibagi-bagikan kepada orang-orang kaya pula. Yang katanya, sebagai simbol penolak bala, sekaligus sebagai harapan agar dalam mengarungi hidup berumah rangga, pengantin dikaruniai rezeki (kekayaan) berlimpah dan survive. Atau, kekayaan memang simbol kembang, yang kelak layu dan mati? Atau, inikah “menjadi kaya itu mulia”?
Mari bertanya pada Sulaeman dan Qorun. n rizagana
Tulisan ini telah dimuat di Investor Daily edisi Selasa 19 September 2006 halaman 24
Rubrik RASAN
“Menjadi kaya itu mulia.” Demikian pastor, pendeta dan guru-guru ngaji berkotbah di mana-mana. Mereka mencontohkan Nabi Sulaeman, yang kaya raya. Banyak pula orang yang mengingikuti. Dengan kekayaannya, mereka ikhlas bersedekah, menolong anak yatim dan orang miskin-papa, membangun rumah ibadah, beribadah, dan beramal yang lainnya.
“Menjadi kaya itu mulia.” Banyak orang, dulu dan sekarang, berkata begitu. Mereka pun berlomba-lomba mencari kekayaan dengan cara-cara mulia atau tidak mulia. Dengan kekayaan, ia bisa meraih ketenaran. Masuk koran, majalah, tv, apalagi tercatat sebagai orang terkaya sejagad. Dengan kekayaan itu juga ia bisa membangun rumah mewah, menyekolahkan anak di sekolah mahal, bahkan di luar negeri, membeli mobil-mobil mewah, membeli ijazah lewat jalan pintas, hingga meraih kekuasaan.
Qorun di jaman Nabi Musa --keduanya masih sepupu(?)--barangkali, berkata begitu juga. “Menjadi kaya itu mulia.” Bahkan ia tidak menerima kemuliaan anak pamannya itu sebelum akhirnya ditelan bumi. Sekarang, setiap orang yang mendapat harta tak bertuan dari dalam bumi disebut harta karun. Atau Robin Hood. Hikayat dari Inggris yang terkenal di seluruh jagad ini, bisa jadi menganggap, “menjadi kaya itu mulia.” Sehingga ia silap mata, dan rela menjadi tumbal peradaban. Ia ingin orang-orang miskin bisa jadi kaya, menikmati ‘kemuliaan’ seperti orang-orang kaya.
Rasanya, tak ada yang menyangsikan “menjadi kaya itu mulia.” Oleh karena itu, banyak orang yang mengejar dan meraihnya dengan cara apa dan bagaimana pun. Mulia atau tidak. Dan, banyak orang membelanjakannya dengan cara apa pun pula. Mulia atau tidak. Untuk kenyamanan, keamanan, kehormatan, dan ketenaran. Untuk bergaul dengan orang kaya, sekaligus ‘menggauli’ dan ‘memperkosa’ orang-orang miskin, atau yang tak sekaya ia.
“Menjadi kaya itu mulia.” Tapi tak sedikit pula yang mengatakan, “menjadi miskin itu mulia.” Lalu kata-kata itu dibolak-balik. Bingung dan membingungkan. Antara kemuliaan di kehidupan ini dan setelah ini. Antara kemuliaan dan kehinaan. Antara siapa yang kaya, dan siapa yang miskin. Seperti apa yang terjadi belakangan ini.
Ketika jutaan orang berjuang dalam kemiskinan, mengumpulkan uang recehan, uang logam cepe’-an, di jalan-jalan, di pasar-pasar tradisional, di sekolah-sekolah, di pelosok-pelosok untuk menyambung hidup. Ketika jutaan orang habis-habisan dihantam gempa, disapu badai tsunami, ditimpa tanah longsor, diusir lumpur panas. Ketika negeri ini berteriak miskin, lalu membagi beban kemiskinan itu kepada 220 juta rakyat dalam bentuk kenaikan harga BBM dan harga-harga lain, minta-minta orang asing datang dan berinvestasi, mengutang ke sana kemari. Ketika jutaan rakyat berebut jatah bulanan sebesar Rp 100.000 dari pemerintah sebagai kompensasi BBM.
Dan, ketika ada sebuah pesta pernikahan yang membagikan kembang uang kertas senilai Rp 70.000 dan dibagi-bagikan kepada orang-orang kaya pula. Yang katanya, sebagai simbol penolak bala, sekaligus sebagai harapan agar dalam mengarungi hidup berumah rangga, pengantin dikaruniai rezeki (kekayaan) berlimpah dan survive. Atau, kekayaan memang simbol kembang, yang kelak layu dan mati? Atau, inikah “menjadi kaya itu mulia”?
Mari bertanya pada Sulaeman dan Qorun. n rizagana
Tulisan ini telah dimuat di Investor Daily edisi Selasa 19 September 2006 halaman 24
Rubrik RASAN
Monday, September 11, 2006
Pengusaha
“SELAMAT, Papa! Sekali lagi, Selamat! Papa masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia.
Lembaga yang membuat peringkat itu menyebut harta kekayaan Papa sampai triliunan rupiah. Hebat juga lembaga itu. Saya, yang anak Papa saja tak tahu persis berapa kekayaan Papa. Memang perusahaan Papa banyak dan tersebar di seluruh Tanah Air, bahkan di luar negeri.
Papa! Saya kagum pada Papa. Saya kagum dengan tangan bisnis Papa yang cemerlang, yang penuh dengan ide-ide brilian. Saya kagum dengan kesungguhan, kegigihan, dan kerja keras Papa. Saya lebih kagum lagi, karena ide dan kerja keras Papa itu benar-benar bisa direalisasikan. Ada bank yang percaya, ada orang yang mau bekerja sesuai dengan keinginan Papa, dan produk itu laku bak kacang goreng. Sungguh, saya benar-benar kagum!
Saya kagum dengan cara-cara Papa saat berhadapan dengan para pejabat negeri ini. Birokrat atau aparat, pejabat tinggi atau rendahan. Papa, bahkan bisa dekat dengan partai politik mana pun, dan calon-calon presiden, menteri, bahkan pejabat eselon I hingga IV. Birokrat atau aparat. Tak peduli, dia idola atau bukan; dia calon Papa atau bukan. Beda sekali saat menghadapi bawahan. Bahkan, Papa tak sungkan-sungkan membawakan segelas air putih untuk pejabat yang sedang makan pada acara standing party. Papa bisa menenggelamkan ego, demi sebuah ambisi (bisnis) yang Papa geluti.
Papa benar-benar pengusaha tulen yang sukses. Papa merintisnya dari modal kecil, dari usaha asongan nun jauh dari Jakarta. Pelan tapi pasti, Papa akhirnya bisa seperti sekarang. Lima puluh tahun bukan waktu yang sedikit. Dan, Papa bukan pengusaha yang sedikit-sedikit merengek minta insentif, sebentar-sebentar mengeluhkan kebijakan pemerintah. Papa, selama yang saya tahu, tak pernah mempersoalkan aturan baru yang dikeluarkan pemerintah. Tapi, heran saya, Papa selalu lebih dulu tahu tentang aturan yang akan keluar. Lalu, Papa tahu di mana kelemahan aturan itu.
Dalam bisnis, Papa seng ada lawan. Tak ada angin, tak ada hujan, Papa menginstrusikan anak buah membeli tanah di suatu daerah. Heran! Caranya terserah! Negosiasi baik-baik, menyogok kepala desa, atau mengerahkan preman. Papa memang tidak seperti Presiden AS yang membombardir sebuah negeri dengan ratusan, bahkan ribuah bom, rudal, roket, dan mesiu, serta membunuh ribuan orang dan membuat jutaan orang jadi miskin papa dengan alasan yang tak pernah terbukti, kecuali di negeri itu ada tanah, minyak dan harta kekayaan orang.
Papa pasti tidak seperti itu, meski ada juga yang kemudian melarat atau mati. Papa lebih mirip Raja Midas, karena apa yang ada di tangan Papa pasti berubah dan berbuah jadi emas. Tanah belukar, rawa-rawa, terpencil di pelosok, tak bersurat lengkap, Papa sulap menjadi real estate mewah. Tanah yang dibeli seharga Rp 1.000 per meter persegi, laku terjual dengan harga seribu kali lipat, bahkan lebih. Itu tanah ratusan, malah ribuan hektare.
Papa tahu benar daerah mana yang bakal maju, wilayah mana yang akan dilalui jalan tol, lokasi mana yang kelak jadi kota baru atau pusat bisnis. Inilah kebodohan orang-orang kampung nan miskin itu, sekaligus menjadi kehebatan Papa. Ah, Papa pasti paham betul apa yang disebut Hernando de Soto dengan The Mystery of Capital-nya.
Papa, banyak orang terpelajar dan cerdas, serta kaya di negeri ini. Tapi tak banyak yang bisa seperti Papa. Termasuk saya, Papa!
Jangan marah, Papa! Saya harus jujur pada Papa, dan diri sendiri bahwa saya tak bisa dan takkan mungkin bisa menjadi pengusaha, seperti Papa. Saya pasti tak sehebat Papa. Dalam menjalankan bisnis, membuat konsep dan ide yang brilian, menghadapi pejabat dan aparat, karyawan, wartawan, dan warga yang terusir menjadi miskin dan melarat. Jujur, Papa, saya katakan!
Sekali lagi, jangan marah, Papa! Maaf, kalau saya terpaksa harus jujur pada Papa. Toh masih banyak profesional, orang kepercayaan Papa. Maaf, sekali lagi maaf! Bukan saya tidak mau menjadi orang kaya, masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia, bahkan di dunia. Bukan pula saya tak suka kemasyhuran. Saya cuma ingin jujur pada diri sendiri. Seperti yang Papa ajarkan. ‘Lihatlah ke dalam. Kalau kau melihat ke luar, kau tak tahu kemana kau melangkah. Melihat ke luar adalah bermimpi. Melihat ke dalam membuat kau terjaga.’
Demikian saja, Papa, surat ananda. Maafkan saya!”
Surat seorang anak kepada pengusaha Indonesia itu tak bertanda tangan, tak bernama. n rizagana
Tulisan ini telah dimuat di Investor Daily edisi Selasa, 12 September 2006 halaman 24
Rubrik RASAN
Lembaga yang membuat peringkat itu menyebut harta kekayaan Papa sampai triliunan rupiah. Hebat juga lembaga itu. Saya, yang anak Papa saja tak tahu persis berapa kekayaan Papa. Memang perusahaan Papa banyak dan tersebar di seluruh Tanah Air, bahkan di luar negeri.
Papa! Saya kagum pada Papa. Saya kagum dengan tangan bisnis Papa yang cemerlang, yang penuh dengan ide-ide brilian. Saya kagum dengan kesungguhan, kegigihan, dan kerja keras Papa. Saya lebih kagum lagi, karena ide dan kerja keras Papa itu benar-benar bisa direalisasikan. Ada bank yang percaya, ada orang yang mau bekerja sesuai dengan keinginan Papa, dan produk itu laku bak kacang goreng. Sungguh, saya benar-benar kagum!
Saya kagum dengan cara-cara Papa saat berhadapan dengan para pejabat negeri ini. Birokrat atau aparat, pejabat tinggi atau rendahan. Papa, bahkan bisa dekat dengan partai politik mana pun, dan calon-calon presiden, menteri, bahkan pejabat eselon I hingga IV. Birokrat atau aparat. Tak peduli, dia idola atau bukan; dia calon Papa atau bukan. Beda sekali saat menghadapi bawahan. Bahkan, Papa tak sungkan-sungkan membawakan segelas air putih untuk pejabat yang sedang makan pada acara standing party. Papa bisa menenggelamkan ego, demi sebuah ambisi (bisnis) yang Papa geluti.
Papa benar-benar pengusaha tulen yang sukses. Papa merintisnya dari modal kecil, dari usaha asongan nun jauh dari Jakarta. Pelan tapi pasti, Papa akhirnya bisa seperti sekarang. Lima puluh tahun bukan waktu yang sedikit. Dan, Papa bukan pengusaha yang sedikit-sedikit merengek minta insentif, sebentar-sebentar mengeluhkan kebijakan pemerintah. Papa, selama yang saya tahu, tak pernah mempersoalkan aturan baru yang dikeluarkan pemerintah. Tapi, heran saya, Papa selalu lebih dulu tahu tentang aturan yang akan keluar. Lalu, Papa tahu di mana kelemahan aturan itu.
Dalam bisnis, Papa seng ada lawan. Tak ada angin, tak ada hujan, Papa menginstrusikan anak buah membeli tanah di suatu daerah. Heran! Caranya terserah! Negosiasi baik-baik, menyogok kepala desa, atau mengerahkan preman. Papa memang tidak seperti Presiden AS yang membombardir sebuah negeri dengan ratusan, bahkan ribuah bom, rudal, roket, dan mesiu, serta membunuh ribuan orang dan membuat jutaan orang jadi miskin papa dengan alasan yang tak pernah terbukti, kecuali di negeri itu ada tanah, minyak dan harta kekayaan orang.
Papa pasti tidak seperti itu, meski ada juga yang kemudian melarat atau mati. Papa lebih mirip Raja Midas, karena apa yang ada di tangan Papa pasti berubah dan berbuah jadi emas. Tanah belukar, rawa-rawa, terpencil di pelosok, tak bersurat lengkap, Papa sulap menjadi real estate mewah. Tanah yang dibeli seharga Rp 1.000 per meter persegi, laku terjual dengan harga seribu kali lipat, bahkan lebih. Itu tanah ratusan, malah ribuan hektare.
Papa tahu benar daerah mana yang bakal maju, wilayah mana yang akan dilalui jalan tol, lokasi mana yang kelak jadi kota baru atau pusat bisnis. Inilah kebodohan orang-orang kampung nan miskin itu, sekaligus menjadi kehebatan Papa. Ah, Papa pasti paham betul apa yang disebut Hernando de Soto dengan The Mystery of Capital-nya.
Papa, banyak orang terpelajar dan cerdas, serta kaya di negeri ini. Tapi tak banyak yang bisa seperti Papa. Termasuk saya, Papa!
Jangan marah, Papa! Saya harus jujur pada Papa, dan diri sendiri bahwa saya tak bisa dan takkan mungkin bisa menjadi pengusaha, seperti Papa. Saya pasti tak sehebat Papa. Dalam menjalankan bisnis, membuat konsep dan ide yang brilian, menghadapi pejabat dan aparat, karyawan, wartawan, dan warga yang terusir menjadi miskin dan melarat. Jujur, Papa, saya katakan!
Sekali lagi, jangan marah, Papa! Maaf, kalau saya terpaksa harus jujur pada Papa. Toh masih banyak profesional, orang kepercayaan Papa. Maaf, sekali lagi maaf! Bukan saya tidak mau menjadi orang kaya, masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia, bahkan di dunia. Bukan pula saya tak suka kemasyhuran. Saya cuma ingin jujur pada diri sendiri. Seperti yang Papa ajarkan. ‘Lihatlah ke dalam. Kalau kau melihat ke luar, kau tak tahu kemana kau melangkah. Melihat ke luar adalah bermimpi. Melihat ke dalam membuat kau terjaga.’
Demikian saja, Papa, surat ananda. Maafkan saya!”
Surat seorang anak kepada pengusaha Indonesia itu tak bertanda tangan, tak bernama. n rizagana
Tulisan ini telah dimuat di Investor Daily edisi Selasa, 12 September 2006 halaman 24
Rubrik RASAN
Tuesday, September 05, 2006
Misteri de Soto
BAMBANG membanting koran. Yusuf, tetangga gang sebelah, yang kebetulan lewat, terkesiap. “Ada apa Pak? Koran kok dibanting!” Yusuf, lalu mampir, bertamu.
Bambang tak menjawab, kecuali mempersilakan tamunya masuk dan duduk lesehan di beranda. Ia memungut kembali koran hari itu, Sabtu, 2 September 2006. Di situ terpampang berita; pemerintah akhirnya memutuskan impor beras sebanyak 210.000 ton pada tahun ini. Pada halaman lain, terpampang foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, dan Gubernur Kalimantan Tengah yang mantan anggota DPR Teras Narang panen raya di lahan gambut Kapuas, Kalteng.
Masih koran yang sama, ada berita yang menyebutkan, pemerintah menganggarkan dana untuk penanggulangan kemiskinan pada 2005 sebesar Rp 22 triliun. Tahun ini naik menjadi Rp 42 triliun, dan tahun depan menjadi Rp 51 triliun. Anggaran penanggulangan kemiskinan naik terus, tapi jumlah orang miskin juga naik. Tahun ini naik 10% dibanding tahun lalu menjadi 39,05 juta atau 17,75% dari total penduduk 222 juta jiwa. “Lantas kemana larinya dana-dana itu?”
Bambang menyilangkan jari-jemari tangan dan menangkupkannya di ubun-ubun. Tiba-tiba Yudho, anaknya, datang sembari bersiul. “Apakabar, Om? Aku dengar, seru sekali bicara tentang kemiskinan dan orang miskin, Om?” Yudho menyalami tamu dan bapaknya, dan menggamit sebuah buku.
“Buku apa itu Do?” tanya Ucup.
“Ini! Ini buku bagus, dan cocok tentang tema diskusi di sini!” Yudho lalu menjelaskan buku yang baru ia pinjam dari temannya. Ia belum baca, tapi temannya sudah bercerita tentang isinya secara garis besar. Buku yang bercerita tentang orang miskin yang sebenarnya kaya raya. “Tapi dasar orang miskin, ia tak tahu bahwa ia kaya. Di sinilah misterinya.”
Ketika Ucup ingin mengambil buku itu, dengan sigap Yudho ngeles. Sambil menunjuk-nunjuk buku itu, Yudho mengatakan, ada miliaran orang miskin di dunia ini dan 80%-nya tinggal di negara Dunia Ketiga dan bekas komunis. Mereka rata-rata hidup di rumah dan tanah secara ilegal. Kalau diuangkan, total nilai real estate orang-orang miskin di seluruh dunia yang dimiliki secara ilegal itu mencapai US$ 9,3 triliun.
Dua orang tua itu terperangah. "Sembilan koma tiga triliun dolar Amerika?"
Ya! Jumlah itu hampir sama dengan nilai total semua perusahaan yang tercantum pada 20 bursa saham utama di negara paling maju sedunia; New York, Tokyo, London, Frankfurt, Toronto, Paris, Milan, Nasdaq, dan selusin lainnya. Nilai ‘kekayaan’ orang miskin sedunia itu sama dengan 20 kali total investasi langsung asing (FDI) di negara Dunia Ketiga dan bekas komunis dalam 10 tahun sejak 1989, 46 kali nilai semua pinjaman negara dari Bank Dunia selama tiga dekade terakhir, dan 93 kali bantuan untuk perkembangan dari semua negara maju kepada Dunia Ketiga dan bekas komunis dalam periode yang sama.
Di Haiti, di Peru, di Filipina, di Mesir, dan di Indonesia demikian juga. Tapi, kata Yudho, sekali lagi, tapi orang miskin tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa di rumah mereka itu ada tambang berlian. Mereka tidak tahu, seperti kata Einstein, tumpukan batu bata sesungguhnya bisa menghasilkan energi atom, seperti yang meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki. Mereka tidak tahu bagaimana aset yang mereka miliki itu bisa dikonversi menjadi modal yang bisa membuat mereka kaya raya.
“Orang-orang di negara Dunia Ketiga dan bekas komunis hanya tahu bagaimana melindungi aset berupa tanah dan rumah, dll. Ia tetap kapital mati. Di Barat, aset itu diolah secara formal dalam dokumentasi yang terus-menerus disesuaikan dengan perkembangan dan diatur oleh peraturan yang terdapat dalam sistem property.”
“Itulah kuncinya!”
“Buku apa itu, Do?” Ucup memiringkan kepalanya ketika Yudho menunjukkan buku The Mystery of the Capital, karya Hernando de Soto itu. Ucup melirik Bambang, lalu berucap, “Oo, Misteri Soto!”
“Kabarmu sendiri, gimana, Do? Sudah dapat kerja?” Ucup, lalu merebut buku itu.
“Belum, Om!” Kali ini, Yudho senyum kecut. Sudah dua tahun ia diwisuda sebagai sarjana ekonomi dari sebuah perguruan tinggi swasta terkenal.
“Ijazahmu itu, property bukan, Do?” kata Ucup, lalu menaruh buku itu setengah dibanting. n rizagana
Tulisan ini telah dimuat di Investor Daily edisi Selasa, 5 September 2006 halaman 24
Rubrik RASAN
Bambang tak menjawab, kecuali mempersilakan tamunya masuk dan duduk lesehan di beranda. Ia memungut kembali koran hari itu, Sabtu, 2 September 2006. Di situ terpampang berita; pemerintah akhirnya memutuskan impor beras sebanyak 210.000 ton pada tahun ini. Pada halaman lain, terpampang foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, dan Gubernur Kalimantan Tengah yang mantan anggota DPR Teras Narang panen raya di lahan gambut Kapuas, Kalteng.
Masih koran yang sama, ada berita yang menyebutkan, pemerintah menganggarkan dana untuk penanggulangan kemiskinan pada 2005 sebesar Rp 22 triliun. Tahun ini naik menjadi Rp 42 triliun, dan tahun depan menjadi Rp 51 triliun. Anggaran penanggulangan kemiskinan naik terus, tapi jumlah orang miskin juga naik. Tahun ini naik 10% dibanding tahun lalu menjadi 39,05 juta atau 17,75% dari total penduduk 222 juta jiwa. “Lantas kemana larinya dana-dana itu?”
Bambang menyilangkan jari-jemari tangan dan menangkupkannya di ubun-ubun. Tiba-tiba Yudho, anaknya, datang sembari bersiul. “Apakabar, Om? Aku dengar, seru sekali bicara tentang kemiskinan dan orang miskin, Om?” Yudho menyalami tamu dan bapaknya, dan menggamit sebuah buku.
“Buku apa itu Do?” tanya Ucup.
“Ini! Ini buku bagus, dan cocok tentang tema diskusi di sini!” Yudho lalu menjelaskan buku yang baru ia pinjam dari temannya. Ia belum baca, tapi temannya sudah bercerita tentang isinya secara garis besar. Buku yang bercerita tentang orang miskin yang sebenarnya kaya raya. “Tapi dasar orang miskin, ia tak tahu bahwa ia kaya. Di sinilah misterinya.”
Ketika Ucup ingin mengambil buku itu, dengan sigap Yudho ngeles. Sambil menunjuk-nunjuk buku itu, Yudho mengatakan, ada miliaran orang miskin di dunia ini dan 80%-nya tinggal di negara Dunia Ketiga dan bekas komunis. Mereka rata-rata hidup di rumah dan tanah secara ilegal. Kalau diuangkan, total nilai real estate orang-orang miskin di seluruh dunia yang dimiliki secara ilegal itu mencapai US$ 9,3 triliun.
Dua orang tua itu terperangah. "Sembilan koma tiga triliun dolar Amerika?"
Ya! Jumlah itu hampir sama dengan nilai total semua perusahaan yang tercantum pada 20 bursa saham utama di negara paling maju sedunia; New York, Tokyo, London, Frankfurt, Toronto, Paris, Milan, Nasdaq, dan selusin lainnya. Nilai ‘kekayaan’ orang miskin sedunia itu sama dengan 20 kali total investasi langsung asing (FDI) di negara Dunia Ketiga dan bekas komunis dalam 10 tahun sejak 1989, 46 kali nilai semua pinjaman negara dari Bank Dunia selama tiga dekade terakhir, dan 93 kali bantuan untuk perkembangan dari semua negara maju kepada Dunia Ketiga dan bekas komunis dalam periode yang sama.
Di Haiti, di Peru, di Filipina, di Mesir, dan di Indonesia demikian juga. Tapi, kata Yudho, sekali lagi, tapi orang miskin tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa di rumah mereka itu ada tambang berlian. Mereka tidak tahu, seperti kata Einstein, tumpukan batu bata sesungguhnya bisa menghasilkan energi atom, seperti yang meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki. Mereka tidak tahu bagaimana aset yang mereka miliki itu bisa dikonversi menjadi modal yang bisa membuat mereka kaya raya.
“Orang-orang di negara Dunia Ketiga dan bekas komunis hanya tahu bagaimana melindungi aset berupa tanah dan rumah, dll. Ia tetap kapital mati. Di Barat, aset itu diolah secara formal dalam dokumentasi yang terus-menerus disesuaikan dengan perkembangan dan diatur oleh peraturan yang terdapat dalam sistem property.”
“Itulah kuncinya!”
“Buku apa itu, Do?” Ucup memiringkan kepalanya ketika Yudho menunjukkan buku The Mystery of the Capital, karya Hernando de Soto itu. Ucup melirik Bambang, lalu berucap, “Oo, Misteri Soto!”
“Kabarmu sendiri, gimana, Do? Sudah dapat kerja?” Ucup, lalu merebut buku itu.
“Belum, Om!” Kali ini, Yudho senyum kecut. Sudah dua tahun ia diwisuda sebagai sarjana ekonomi dari sebuah perguruan tinggi swasta terkenal.
“Ijazahmu itu, property bukan, Do?” kata Ucup, lalu menaruh buku itu setengah dibanting. n rizagana
Tulisan ini telah dimuat di Investor Daily edisi Selasa, 5 September 2006 halaman 24
Rubrik RASAN
Subscribe to:
Posts (Atom)