“MENJADI kaya itu mulia.” Kata-kata itu bergaung ke seluruh dataran Cina. Deng Xiao Ping menggunakan kalimat itu untuk menggantikan slogan yang sebelumnya dikumandangkan Mao Zhedong dari ajaran Marxis, “sama rata, sama rasa.” Sejak itu, negeri Tirai Bambu itu memangkas habis semua rumpun bambu dan menggantikannya dengan jalan mulus bebas hambatan, pabrik-pabrik, apartemen, perumahan, dan gedung-gedung perkantoran. Miliaran rakyat (negara) Cina berlomba-lomba mengejar kekayaan. Juga kemuliaan?
“Menjadi kaya itu mulia.” Demikian pastor, pendeta dan guru-guru ngaji berkotbah di mana-mana. Mereka mencontohkan Nabi Sulaeman, yang kaya raya. Banyak pula orang yang mengingikuti. Dengan kekayaannya, mereka ikhlas bersedekah, menolong anak yatim dan orang miskin-papa, membangun rumah ibadah, beribadah, dan beramal yang lainnya.
“Menjadi kaya itu mulia.” Banyak orang, dulu dan sekarang, berkata begitu. Mereka pun berlomba-lomba mencari kekayaan dengan cara-cara mulia atau tidak mulia. Dengan kekayaan, ia bisa meraih ketenaran. Masuk koran, majalah, tv, apalagi tercatat sebagai orang terkaya sejagad. Dengan kekayaan itu juga ia bisa membangun rumah mewah, menyekolahkan anak di sekolah mahal, bahkan di luar negeri, membeli mobil-mobil mewah, membeli ijazah lewat jalan pintas, hingga meraih kekuasaan.
Qorun di jaman Nabi Musa --keduanya masih sepupu(?)--barangkali, berkata begitu juga. “Menjadi kaya itu mulia.” Bahkan ia tidak menerima kemuliaan anak pamannya itu sebelum akhirnya ditelan bumi. Sekarang, setiap orang yang mendapat harta tak bertuan dari dalam bumi disebut harta karun. Atau Robin Hood. Hikayat dari Inggris yang terkenal di seluruh jagad ini, bisa jadi menganggap, “menjadi kaya itu mulia.” Sehingga ia silap mata, dan rela menjadi tumbal peradaban. Ia ingin orang-orang miskin bisa jadi kaya, menikmati ‘kemuliaan’ seperti orang-orang kaya.
Rasanya, tak ada yang menyangsikan “menjadi kaya itu mulia.” Oleh karena itu, banyak orang yang mengejar dan meraihnya dengan cara apa dan bagaimana pun. Mulia atau tidak. Dan, banyak orang membelanjakannya dengan cara apa pun pula. Mulia atau tidak. Untuk kenyamanan, keamanan, kehormatan, dan ketenaran. Untuk bergaul dengan orang kaya, sekaligus ‘menggauli’ dan ‘memperkosa’ orang-orang miskin, atau yang tak sekaya ia.
“Menjadi kaya itu mulia.” Tapi tak sedikit pula yang mengatakan, “menjadi miskin itu mulia.” Lalu kata-kata itu dibolak-balik. Bingung dan membingungkan. Antara kemuliaan di kehidupan ini dan setelah ini. Antara kemuliaan dan kehinaan. Antara siapa yang kaya, dan siapa yang miskin. Seperti apa yang terjadi belakangan ini.
Ketika jutaan orang berjuang dalam kemiskinan, mengumpulkan uang recehan, uang logam cepe’-an, di jalan-jalan, di pasar-pasar tradisional, di sekolah-sekolah, di pelosok-pelosok untuk menyambung hidup. Ketika jutaan orang habis-habisan dihantam gempa, disapu badai tsunami, ditimpa tanah longsor, diusir lumpur panas. Ketika negeri ini berteriak miskin, lalu membagi beban kemiskinan itu kepada 220 juta rakyat dalam bentuk kenaikan harga BBM dan harga-harga lain, minta-minta orang asing datang dan berinvestasi, mengutang ke sana kemari. Ketika jutaan rakyat berebut jatah bulanan sebesar Rp 100.000 dari pemerintah sebagai kompensasi BBM.
Dan, ketika ada sebuah pesta pernikahan yang membagikan kembang uang kertas senilai Rp 70.000 dan dibagi-bagikan kepada orang-orang kaya pula. Yang katanya, sebagai simbol penolak bala, sekaligus sebagai harapan agar dalam mengarungi hidup berumah rangga, pengantin dikaruniai rezeki (kekayaan) berlimpah dan survive. Atau, kekayaan memang simbol kembang, yang kelak layu dan mati? Atau, inikah “menjadi kaya itu mulia”?
Mari bertanya pada Sulaeman dan Qorun. n rizagana
Tulisan ini telah dimuat di Investor Daily edisi Selasa 19 September 2006 halaman 24
Rubrik RASAN
Tuesday, September 19, 2006
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
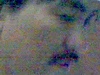
No comments:
Post a Comment