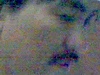MUDIK. Meninggalkan Jakarta dan kemacetannya. Menjauhi kesibukan dan tekanan dead line dan portofolio saham yang tiap hari menerjang pikiran. Menjelang Gema Takbir, menyongsong kampung kelahiran dan masa-masa remaja.
Di tengah pasar, di kelilingi hijau sawah-sawah yang membentang, di sisi sungai kecil jaringan irigasi yang setiap 3-5 kilometer dibendung agar mengairi sawah-sawah milik penduduk.
Di antarkan jalan beraspal mulus di sisi sungai kecil yang disodet dari Sungai Komering itu. Itu adalah jalan masuk ke kampung, setelah 24 jam (hari biasa cuma 12 jam) menyusuri Jakarta-Merak-Bakauheuni-Bandar Lampung-Kotabumi-Bukit Kemuning-Martapura-Belitang.
Di gerbang Belitang, sebuah tugu raksasa bertuliskan Selamat Datang di Kota Terpadu Mandiri (KTM). Sejak kapan? Bukankah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno baru saja mengumandangkannya?
Deru sepeda motor menyesaki jalan, beriring-iringan, memagari setiap mobil yang lewat. Dulu, tiga tahun lalu, cuma ada beberapa sepeda motor, selebihnya adalah iring-iringan sepeda angin. Kendaraan itulah yang mengantarkan mereka ke sekolah, berniaga ke pasar, atau mengunjungi handai-tolan.
Memasuki Gumawang, ibukota Kecamatan Belitang, rumah-rumah toko yang dulu bertingkat papan dan kayu, kini full beton. Toko-toko pun makin beragam. Mulai dari handphone dan asesorinya hingga dealer motor berjejer. Ada juga toko elektronika, termasuk komputer dan laptop. Di sisi lain berjejer toko grosir untuk beragam barang diselingi kantor bank, Bank Sumsel atau BRI.
Tiga tahun lalu masih ada kawan atau kerabat yang menanyakan mobil yang dibawa ke kampung. (Padahal yang dibawa mobil sewaan). Kali ini tidak ada. Mobil mereka lebih mewah, bahkan mereka punya lebih dari satu mobil. Kijang Inova, Honda CRV hingga Mitsubishi double cabin.
Bangga bercampur heran. Ada apa gerangan dengan (perekonomian) kampung yang berjarak 120 kilometer dari Palembang, yang selama ini dijuluki Lumbung Padi Sumatera Selatan itu.
“Karet!” jawab mereka pendek.
Teringat pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika mampir dan shalat Jumat di Masjid Agung Gumawang, Belitang pada 28 Januari 2005. Tepat 100 hari setelah ia dilantik jadi presiden. Ia datang ke kampung itu dalam rangka Panen Raya Padi. “Kita tidak ingin pengusaha kuat makin kuat, sementara petani dan nelayan makin terjepit dan makin miskin,” kata Presiden.
Di sela pidatonya, ia menyebut karet dan kelapa sawit. Ia pun menyerahkan bibit tanaman karet dan kelapa sawit.
Tentu, bukan bibit dari Presiden yang membuat rakyat Belitang makmur seperti itu. Karena karet baru bisa dipanen setelah tanaman karet berusia lima tahun. Paling tidak Presiden sudah mendapat informasi tentang gairah penduduk Belitang menanam karet. Kedatangan Presiden dan pemberian bibit karet dan sawit itu pun tentu tak dimaksudkan agar petani meninggalkan tanam padi.
Tapi kini, karet adalah masa depan petani. Sekarang separuh pendapatan petani di Sumsel berasal dari karet.
Apalagi harga karet dunia saat ini sudah US$ 2,1 per kg. Karet petani di Belitang dihargai separuhnya, cuma Rp 9.000 per kg. Satu hektare tanaman karet bisa menghasilkan dua ton karet per tahun atau setara Rp 18 juta per tahun. Tak sedikit petani yang memiliki 5-10 hektare. Modal awalnya cuma Rp 15-an juta per hektare. Dan, sekali menanam karet, seumur hidup bisa memetik hasil karena tanaman karet bisa dipanen hingga usia 30 tahun. Bagi petani yang memulai usaha pada usia 30 tahun, karet adalah tanaman untuk seumur hidup petani.
Hitung-hitungan pejabat Dinas Perkebunan Sumsel, produksi karet kering Sumsel pada 2006 mencapai 700 ribu ton karet kering per tahun atau hampir 2.000 ton karet per hari. (Produksi karet nasional pada 2006 sekitar 2,1 juta ton). Hampir semuanya diekspor dengan nilai US$ 762 juta per tahun.
Angka itu murni dari karet, belum termasuk upah yang diterima anggota keluarga atau kerabat dan tetangga yang menjadi tenaga pemelihara dan penyadap karet, pengangkut ke truk untuk dikirim ke pembeli, serta buruh-buruh di pabrik karet. Mereka itu semua yang menggerakkan ekonomi Belitang, kampung transmigrasi di perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan. Mereka yang rata-rata tinggal di sekitar kota (sudah bisa disebut kota kah?) Gumawang.
Lamunan pun menerawang jauh hingga ke pelosok kampung lain di Nusantara ini. Teringat cerita teman dari Bojonegoro, Jawa Timur tentang perkebunan tembakau yang pernah ‘memaksa’ petani membeli kulkas untuk lemari pakaian, karena tak ada listrik. Pernah pula membaca berita di koran tentang mobil mewah Pajero yang laris bak kacang goreng di Sulawesi Selatan karena komoditi udang yang lagi naik daun. Kemudian cerita itu hilang ditelan angin.
Ada kekhawatiran dari pejabat di Sumsel tentang komoditas karet ini. Gejolak harga bukan hanya akan memengaruhi penghasilan keluarga Belitang, tapi juga cicilan kredit motor, mobil, dan rumah toko pun bisa tersendat. Harga karet bergejolak, bank bisa tersedak. Ekonomi daerah bisa batuk-batuk.
Kekhawatiran lain adalah hilangnya julukan Lumbung Padi yang selama ini melekat di Belitang karena konversi lahan sawah menjadi karet atau karena tak ada lagi yang mau menanam padi. Akankah presiden mendatang mengunjungi Belitang, seperti pendahulunya dari Soeharto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono untuk panen raya?
“Ah, untuk apa kampung kita selalu didatangi presiden kalau tak ada hasilnya,” sergah seorang teman. Karet kan bisa melar. n rizagana
Tangerang, 18 Oktober 2007
Thursday, October 18, 2007
Subscribe to:
Posts (Atom)