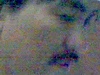Jenderal Nagabonar terisak-isak dan terseok-seok meniti tali menaiki patung Jenderal Soedirman di tengah jalan protokol di Jakarta.
Nagabonar, yang pencopet itu, tidak rela jenderal pujaannya memberi hormat kepada siapa saja di jalan raya yang dipadati kendaraan roda empat. Siapa pula yang dihormati Jenderal Soedirman itu siang dan malam? Pertanyaan yang mirip dilontarkan Nagabonar ketika menyambangi Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. “Apakah semua yang dimakamkan di sini, pahlawan?”
Anak-anak terkekeh-kekeh menyaksikan adegan film dari DVD bajakan yang dibelikan orang tuanya.
Di luar rumahnya, anak-anak bangsa ini juga sedang tertawa terbahak-bahak. Bukan karena tingkah polah Nagabonar. Tapi menertawakan diri sendiri dan orang lain atas tingkah-polah orang asing di negerinya.
Khususnya dalam pekan-pekan terakhir ini. Sebuah perusahaan konglomerat Singapura sedang menunggu vonis dari Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia dan di Jakarta. Melinda Tan, juru lobi Temasek, kembali harus pergi-pulang Jakarta-Singapura. Ini berkaitan dengan dugaan monopoli Temasek dalam industri telekomunikasi Indonesia.
Sebuah perkara yang sudah lama. Paling tidak sejak Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) membeli sekitar 42% saham PT Indosat pada 2002. STT adalah anak usaha Temasek. Jauh sebelumnya, Temasek melalui Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) telah memiliki 35% saham PT Telkomsel. Konglomerat dari Singapura itu dituduh melanggar UU No 5/1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya pasal 27.
Jadilah, sepekan terakhir ini, ditambah pekan ini, berita tentang Temasek menghiasi media massa di Indonesia. Sumbernya rata-rata orang Indonesia, pengamat ekonomi, pejabat, dan tidak ketinggalan anggota DPR. Ada (banyak) yang mendukung Temasek, dengan mengatakan bahwa Temasek tidak melakukan kepemilikan silang (cross ownership). Dan, macam-macam lagi argumentasi yang dikemukakan, menyudutkan anggota KPPU yang sedang bekerja, bahkan sampai menghujat anak bangsa sendiri.
"Apa kata dunia!" kata mereka yang mendukung Temasek. Ini soal investasi asing. Ini tentang kepastian hukum dan berusaha. Ini mengenai anggota KPPU yang dituduh menerima suap.Tapi, tak sedikit pula yang mendukung. Entah, mereka benar-benar mendukung dengan logika berpikir yang jernih dan keilmuwan yang bisa dipertanggungjawabkan. Atau itu sekadar olah vokal, demi menanti royalti dari lagu yang dinyanyikan. Lalu tutup mulut, atau bahkan balik mendukung Temasek dan dengan gagah berani ‘menyerang’ anak bangsa sendiri.
"Apa kata dunia!" Mereka yang mendukung KPPU lantang bersuara. Lebih lantang dan kental logat Medan-nya daripada orang Medan. Ini soal harga diri bangsa. Ini tentang dan mengenai dunia yang sesungguhnya tak bisa berkata-kata.
Apa peduli dan siapa peduli dengan putusan KPPU tentang monopoli Temasek itu, sejatinya? Tak perlu pulalah menyebut siapa yang mendukung, siapa yang menentang. Tak lagi menarik mengatakan, putusan itu akan memengaruhi masuknya investor asing di Indonesia. Soal Singapura, yang katanya banyak ‘menyembunyikan’ konglomerat hitam dan koruptor plus hasil jarahannya itu, juga tak perlu dibahas.
Karena hasil putusan KPPU itu sejatinya menjadi tidak penting lagi dibahas. Apapun putusan yang dijatuhkan oleh KPPU, bangsa ini benar-benar sudah tercabik-cabik. Anak bangsa ini sudah diaduk-aduk dan diadu-domba dengan begitu mudahnya. Gampang sekali. Segampang menumpahkan darah bangsa sendiri.
Ranah pemikiran tidak lagi penting, apakah ia benar secara keilmuwan atau sekadar cuap-cuap agar suap demi suap masuk ke dalam mulutnya. Kebenaran toh bisa disembunyikan di balik baju lembaga yang mentereng, di balik safari jabatan yang tebal, di balik ketiak tuan-tuan berkantung tebal.
Jadi, untuk apa sebenarnya membahas masalah ini. Juga mengada-ada atau bahkan akan ditertawakan secara berirama kalau ada yang bilang, “Hey! Ini menjelang Hari Pahlawan. Tanggal 10 November itu tinggal beberapa hari lagi! Apakah mereka-mereka yang pro dan kontra itu ingin menjadi pahlawan?”
Ah, lebih baik melanjutkan menonton film Nagabonar 2 dari DVD bajakan seharga sepuluh ribu perak. Meski, lama-lama sogan terkenal dari Nagabonar "apa kata dunia" itu tak lucu lagi. Justru adegan pro dan kontra tentang kasus cross ownership itulah yang lucu dan menggelikan sekaligus menyedihkan. o