“Are you Indonesia?”
Seorang pria menyapa dua wanita di salah satu sudut Pulau Sentosa, Singapura, dengan tatapan penuh harap. Kedua wanita itu sedang berbincang dalam bahasa Betawi.
“Yes, we are!” Spontan keduanya menjawab.
“Sama dong!”
Mereka sama-sama menyalahkan, “sudah tahu orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia, masih nanya? Pakai bahasa Inggris pula!”
Lalu mereka padu, berdialog dalam bahasa yang sama, elo-gue. Mereka berjalan beriringan, bercerita, berkeluh kesah.
Belasan tahun berlalu. Perjalanan itu pun mengantarkan mereka ke kampung halamannya. Dan, mereka masih melanjutkan pembicaraan dengan bahasa, bukan bahasa ibu mereka. Juga dengan orang lain. Di lingkungan keluarga, pergaulan, tetangga, dan pekerjaan. Tak apa menggunakan bahasa Inggris ala Tukul di Empat Mata.
“Ini tuntutan globalisasi, bung!”
Nama perusahaan tempat mereka bekerja tidak terkesan mentereng kalau tidak ada embel-embel asing, meski akhirnya disingkat juga agar mudah diingat. Perusahaan besar yang dulu dipaksa Joop Ave, menteri Pariwisata era Soeharto, untuk menggunakan Bahasa akhirnya kembali lagi. Kalau tidak berganti nama, ia berganti pemilik. Nama asing, dan dimiliki orang asing.
Bank-bank yang dulu membanggakan, kini telah milik asing. BCA, Danamon, Niaga, Lippo, BII, Panin, NISP.... Perusahaan telekomunikasi, Indosat, Telkomsel, Exelcomindo.... Perusahaan ritel juga, kecuali Grup Matahari. Usaha tambang, minyak dan gas, jangan ditanya. Negeri ini tengah menyiapkan menggelar karpet merah dalam bentuk aturan atau kebijakan bagi masuknya investasi asing.
Juga bidang-bidang lain, seperti manufaktur semen, tekstil dan produk tekstil. Serta jasa-jasa. Mulai dari perkapalan, teknologi informasi, dan di pasar modal. Ada kekompakan di antara orang-orang pemegang kebijakan dan stafnya, serta para wakil rakyat di DPR untuk ‘membiarkan’ dan menggelarkan karpet Istambul --UU Penanaman Modal, UU Perpajakan, dan UU Ketenagakerjaan, UU Migas, Minerba-- untuk tuan-tuan dari negeri seberang bisa ngerumpi asyik di beranda rumah sambil minum teh, kopi atau susu sambil mencicipi masakan khas Indonesia dan keramahtamahannya. Seolah rumah ini milik mereka, mereka yang atur.
Tapi masih ada BUMN, kan? Itulah yang mengkhawatirkan, sesungguhnya. Pemerintah juga sedang berancang-ancang untuk melego perusahaan milik negara, yang berarti juga milik rakyat dan bangsa ini. Alasannya pun sepele, yakni untuk menambal kekurangan pembiayaian urusan kepemerintahan atau karena BUMN itu kurang terurus.
“Ini kan globalisasi, bung!”
Wilayah negara seperti tanpa batas. Siapa saja bisa keluar-masuk dan bahkan bisa menetap, beranak-pinah, berkuasa, dan ‘menjajah’ lagi. Ketika negara-negara lain sibuk mengatur dan memagari kiprah asing di negaranya, memproteksi produk dalam negeri, sebagian orang Indonesia justru ramai-ramai terbius dolar-dolar yang terbawa arus globalisasi. Demi dapur, kemehawan keluarga, keglamoran hidup, ‘kelangsungan’ usahanya, bahkan demi kekuasaan.
Beras diimpor, pasir laut diekspor, konsentrat tambang yang dikeruk dari tanah tak usahlah diteliti mengandung emas atau tembaga, tak apalah negara lain menggunakan negara tercinta ini untuk transhipment (mengekspor) produknya, biarkan saja barang-barang selundupan membanjiri pasar dalam negeri. Untuk apa repot-repot. Pragmatis saja. Toh tak ada yang tahu. Rakyat? itu pun sudah ada wakilnya di DPR. Mereka cukup dikasih gaji dan tunjangan yang besar plus mesin cuci dan laptop.
Ini bukan lagi monopoli birokrat dan aparat, juga wakil rakyat. Dokter tak peduli pasien sehat, asal koceknya penuh dengan komisi dari produsen obat. Pengacara menganggap keadilan itu ada di dalam dompet. Tukang ojek, pedagang kaki lima membolehkan diri mangkal di mana saja. Juga wartawan benar-benar telah menjadi pilar keempat demokrasi, mengikuti jejak eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semua bisa diatur.
Saudagar dan eksekutifnya melupakan pegawai yang serba kekurangan, kualitas dan keamanan produk yang dijual, serta aturan yang bisa diterabas. Kalau perlu uang perusahaan dimainkan. Suatu kala meneriaki pemerintah, dan menghardik buruh. Kala lain menyanjung mereka dengan nada-nada optimistis yang menggelorakan. Hei, tahukah kalian, pada 2030, ekonomi Indonesia akan menjadi lima negara terbesar di dunia! Tahun lalu, PricewaterHouseCoopers, perusahaan jasa keuangan top dari AS, juga berpendapat seperti itu, meski waktunya adalah 2050.
Apa salahnya mengikuti pola pikir orang asing itu. Mungkin saja ada sambutan dari RI-1, dan bisa menjadi P-1 (penguasa nomor) di Tanah Air, seperti era lalu. Dan, apa salahnya pula kalau ‘aku’ bertanya dalam bahasa Inggris kepada dua cewek berlogat Betawi di Pulau Sentosa itu. Mungkin saja ada sambutan hangat, dan bisa melanjutkan arus gombalisasi itu. n rizagana
Tuesday, March 27, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
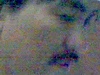
No comments:
Post a Comment