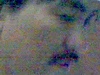Wednesday, July 15, 2009
Bung, Selamat!
Seseorang menyela, dan menghambat langkah salah satu pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009. Penghitungan suara baru saja dimulai. Belum separuh suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu dibuka, si Abang sudah ngeloyor kabur.
“Pulang! Tidur!”
Sejak awal penghitungan suara di TPS itu, keningnya berkerut. Ia tidak menyangka, setiap surat suara dibuka, panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selalu meneriakkan tiga jenis kata, yang maksudnya sama. Yakni, "lanjutkan", “dua” atau “SBY”. Teriakan yang lain hanya sesekali atau malah nyaris tak terdengar.
“Gila!”
Ia mengumpat diri sendiri, dalam suara yang tertahan. Ia tak bisa mengerti, kenapa realita dalam debat capres dan cawapres di televisi dan komentar tokoh-tokoh nasional, ternyata berbeda dengan fakta suara yang menggema di TPS-TPS.
“Lantas, apa gunanya debat capres dan cawapres. Apa artinya komentar tokoh-tokoh nasional di televisi dan koran-koran itu? Pernyataan sekaligus ketetapan hati beberapa tokoh nasional, seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif dan mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie, yang dituangkan dalam tayangan iklan. Bahkan ada yang sampai tega bersumpah demi arwah ibunya?”
“Aku heran....”
Yang lebih heran lagi, ternyata suara JK-Win, sebutan untuk pasangan capres Jusuf Kalla dan cawapres Wiranto, yang digadang-gadang bakal menjadi batu sandungan SBY-Boediono dalam putaran kedua, ternyata kalah dari Mega-Pro, sebutan untuk pasangan capres Megawati Soekarnoputeri dan cawapres Prabowo Subianto. Atau, jangan-jangan fakta itu hanya di TPS tempatnya mencoblos saja....
***
"Lebih cepat memang lebih baik!"
Teman sekantornya menyindir. Dia menoleh ke arah si empunya suara. Tapi belum sempat dia berkomentar, komentar lain muncul dari liang yang sama.
"Maksudku, kalau bisa satu putaran kenapa harus dua putaran!"
Lalu, bergemuruhlah laporan dari beberapa TPS yang disampaikan langsung teman-teman sekantornya. Intinya, pasangan SBY-Boediono memang terlalu 'perkasa' untuk lawan-lawannya.
“Hey, bung! Jawa dan non-Jawa masih punya arti bagi bangsa ini. Sebagai negeri dengan penduduk mayoritas Jawa, siapa sudi dipimpin oleh orang non-Jawa. Bukan bermaksud SARA, tapi demikianlah faktanya, bung!”
Seorang teman mencoba memberikan beberapa argumentasi, dengan gaya yang tak kalah hebat dari para komentator di televisi, yang sering disebut-sebut sebagai tokoh nasional, pengamat, politikus gaek, dan lain sebagainya.
“Itu pertama!"
"Kedua, negeri ini sudah merasa nyaman dan senang dengan keamanan dan kenyamanan yang diberikan selama ini. Paling tidak selama lima tahun terakhir ini. Negeri ini, yang nenek-moyangnya dijajah beratus-ratus tahun, belum membutuhkan pemimpin yang meledak-ledak, apalagi hanya jago berkoar-koar dan senang menepuk dada untuk menunjukkan jati diri (bangsa)....”
“Ketiga. Negeri ini pernah memiliki Soekarno, pemimpin revolusi yang disegani di dalam dan luar negeri, yang kalau berpidato berapi-api. Negeri ini pernah memiliki Soeharto, the Smiling Genderal, yang juga disegani di dalam dan luar negeri, yang kalau pidato biasa-biasa saja. Keduanya menyisakan kisah sedih, bahkan menjadi stigma bagi bangsa ini.”
“Ketahuilah, negeri ini sudah lama menderita. Bahkan sangat menderita. Oleh karena itu, penderitaan akibat kenaikan harga BBM, kehilangan sebuah atau dua buah pulau, bahkan pelecahan atas jati diri bangsa, tak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan yang mendera nenek-moyangnya.”
Si Abang ingin meledakkan suara, rasanya, ketika temannya menguliahinya tentang kenaikan harga BBM, kehilangan pulau, dan terutama tentang jati diri bangsa. Tapi berusaha menekan suaranya di perut dan hatinya. Ia ingin mendengar lebih jauh tentang celoteh komentator yang -seperti komentator bola-- hanya jago mengomentari fakta dengan alibi kalau, seandainya dan seterusnya.
“Untuk mempertahankan sebuah blok di lautan --bukan pulau, lho-- kenapa harus berperang? Kalau masih bisa makan dan mencari nafkah, kenapa harus menyesali kenaikan harga BBM? Kalau ada orang lain lebih mampu menyelesaikan konflik di daerah, kenapa kita harus memaksakan diri untuk tampil. Kalau pemimpin sekarang sudah terbukti memberikan keamanan dan kenyamanan dalam hidup dan kehidupan ini, kenapa harus mempersoalkan neolib? Kalau dan kalau...”
Kalau... dan kalau benar hasil penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan berbagai lembaga riset dan survei itu. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono terpilih sebagai presiden dan wakil presiden ketujuh Republik Indonesia untuk periode 2009-2014.
“Bung, Selamat! Lanjutkan!” Si Abang akhirnya mendekati si komentator dan menyalaminya. Namun, keheranannya masih menyelimuti hati dan pikirannya.
Sebuah prestasi luar biasa. Atau memang banyak orang yang tidak biasa dalam melihat realitas bangsa ini. Mereka yang terlalu lama duduk di ruang-ruang ber-AC dengan suguhan Lemon Tea atau Cappucino Latte dan sambil mengumbar teori-teori moderen tentang kepemimpinan. Tidak banyak, mungkin hanya segelintir. Tapi suara-suara itu digemakan lewat corong-corong yang bernama koran, majalah, radio, televisi, dengan bahasa yang rada njlimet agar mereka yang nun di sana, yang masih akrab dengan teh dan kopi bisa beralih ke Lemon Tea atau Black Cappucino.
Monday, June 29, 2009
'Pembodohan' Nasional
Yang ditanya mengangguk sehingga penanya memberondongnya dengan pertanyaan lain.
"Berapa NEM-nya?"
'Empat puluh enam koma lapan! Kalau anakmu, si Ucup, lulus juga? Berapa NEM-nya?"
"Lulus lah. 54,9!"
"Wah, hebat dong. Berarti rata-ratanya sembilan lebih!"
"Hebat apanya? Wong 60% jawaban soalnya sudah diisi."
"Iya sih! Dina juga cerita, waktu ujian, dia boleh bawa hp. Waktu ngerjain soal tiba-tiba ada SMS. Dia gak tau SMS dari siapa. Tapi isinya adalah jawaban soal ujian. Ha...ha..ha...."
Berdua tertawa. Pendengar lain ikut tertawa.
"Itu karena sekolah punya target agar semua siswanya lulus 100%. Demi nama baik sekolah dan demi nama baik guru-gurunya."
Inilah percakapan yang tersiar di warung kopi. Entah benar atau tidak, faktanya ada beberapa sekolah yang karena salah kasih bocoran jawaban akhirnya 100% siswanya tak lulus.
Apa yang sesungguhnya diharapkan dari program ujian nasional itu kalau sesungguhnya menjadi program penghancuran generasi muda Indonesia. Demi nama sekolah. Demi makin banyaknya siswa baru yang mendaftar. Demi kocek sekolah, saku yayasan dan pengurusnya. Ujung-ujungnya duit juga.
Ada yang hanya diam mendengar obrolan warung kopi itu. Ia ingin segera pulang menanyai anaknya.
"Tapi untuk apa?" Ia bergumam.
Nilai bagus atau jelek, ia juga tak kuasa. Ia tak ada kemampuan untuk melanjutkan sekolah anaknya ke perguruan tinggi.
Bagaimana mau ke perguruan tinggi kalau uang mukanya puluhan juta. Belum lagi uang SPP semesteran atau tahunan yang juga juta-jutaan.
"Aahh....!"
Ia teringat 27 tahun silam ketika ia lulus dari SMA di sebuah kampung di Sumatera Selatan dan mendapat undangan dari Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Andi Hakim Nasution. Orang tuanya senangnya bukan main karena cita-citanya dulu kesampaian juga, meski lewat anaknya.
Waktu itu, ayahnya sadar akan kemampuannya membiayai sekolah di perguruan tinggi, seperti keinginannya di era tahun 50-an. Kali ini, dengan tekad bulat, sang ayah mengirim juga anaknya ke Bogor. Untunglah tak ada uang pangkal. SPP-nya pun cuma Rp 22.500 per semester. Biaya hidup ketika itu cuma Rp 30.000 per bulan, termasuk uang kos-kosan.
"Berangkatlah kau anakku. Berangkatlah ke Bogor. Bapak akan usahakan biayanya."
Kini anak itu sudah menyandang gelar insinyur dan sudah bekerja di Jakarta. Dan, giliran insinyur itu yang mengurut dada memikirkan nasib anaknya yang baru saja lulus SMA.
"Gila. Bapakku dulu, hidup di kampung nun jauh di Sumatera Selatan bisa menyekolahkan enam anaknya hingga meraih sarjana semua. Di Jawa. Bapakku hanya lulusan SMP. Aku insinyur, tinggal di pinggiran Jakarta, kini aku bingung menyekolahkan anakku ke perguruan tinggi."
Ia merenung di depan TV sendirian.
"Dulu, orang desa dengan penghasilan pas-pasan bisa menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi. Kini, hanya orang kaya yang bisa meraih gelar sarjana. Edan!"
Sudah pukul 11 malam lewat. Lamunannya terjaga oleh iklan Mendiknas Bambang Soedibjo yang lantang bicara tentang biaya pendidikan SD gratis. SMP menyusul gratis.
"Aaahhh....! Apa sesungguhnya yang dilakukan pemerintah. SD dan SMP digratiskan, tapi menutup rapat orang tak mampu melanjutkan studi hingga ke perguruan tinggi, meski si anak memang pintar."
Ia mematikan TV dan 'mematikan' dirinya sendiri di tempat tidur. Tapi ia tetap tak bisa tidur juga hingga fajar menjelang.
Bogor, 22 Juni 2009
Thursday, May 21, 2009
The CEO Way: 8 Pendekar TI Indonesia

Ini buku pertama ku.
Dua tahun dalam kandungan pikiranku. Menggelayut bak ayunan, antara jadi dan tidak. lanjutkan atau urungkan.
Akhirnya, buku itu tiba juga di bangsal percetakan. Deg-degan... gelisah.... gembira.... senang. berpadu. Persis seperti menanti kelahiran 'anak" pertama.
Inilah dia: The CEO Way: 8 Pendekar TI Indonesia.
Tuesday, January 06, 2009
Depkominfo dan BKPM Bungkam Asing dalam Bisnis Menara (bag. 1 dari 2 tulisan
Tahun 2008, industri telekomunikasi Indonesia, paling tidak dua kali berhadapan dengan regulasi pemerintah tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 111 Tahun 2007. Dua-duanya selalu melibatkan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada kasus pertama, Depkominfo mengeluarkan aturan yang melarang investor asing masuk dalam bisnis menara telekomunikasi, yang bertentangan dengan Perpres DNI. Kedua, Depkominfo tak kuasa saat Qtel berniat mengakuisisi 65% saham PT Indosat tanpa harus memisahkan bisnis jaringan tetapnya. Kedua kasus itu menunjukkan kepada khalayak, betapa semua bisa diatur di negeri ini, sekalipun melanggar aturan.
Pada awal 2008, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh mengeluarkan regulasi tentang Menara Bersama yang tertuang dalam Peraturan Menkominfo No 2/2008. Aturan itu melarang investor asing untuk berbisnis dalam penyediaan menara telekomunikasi.
Aturan itu hadir sebagai kepedulian pemangku kepentingan, Menkominfo, terhadap industri dalam negeri. Dasarnya adalah hampir seluruh belanja modal industri telekomunikasi telah tersedot ke luar negeri dalam bentuk perangkat jaringan infrastruktur hingga perangkat penerima yang ada di konsumen (pesawat telepon genggam). Bahkan, investor asing telah menguasai sebagian besar saham perusahaan telekomunikasi Indonesia.
Itulah yang dikatakan Dirjen Postel Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar saat menjelaskan latar belakang terbitnya aturan menara yang menolak asing itu. Penyediaan menara merupakan lini bisnis yang bisa diusahakan lokal tanpa campur tangan asing. "Saya rasa semua pihak akan solid mendukung aturan menara ini tanpa ada resistensi," kata Basuki.
Namun, persoalannya bukan di situ, melainkan Peraturan Menkominfo itu dianggap menyalahi aturan di atasnya, yakni Perpres No 111/2007 tentang DNI. Oleh karena itu, aturan itu memancing reaksi dari pengusaha nasional. Ketua Umum Komite Pemulihan Ekonomi Nasional Sofyan Wanandi khawatir, hal itu bakal mengganggu iklim investasi di sektor telekomunikasi.
"Kita tidak berhak menutup pintu bisnis menara bagi asing karena jelas-jelas menyalahi UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal. Lagipula, masalah menara tidak diatur dalam DNI," ujar Sofjan Wanandi kala itu.
Ekonom dari CSIS Pande Radja Silalahi, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) ATSI Agus Simorangkir, ekonom dari CSIS Pande Radja Silalahi, dan Wakil Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi lantang menentang Peraturan Menkominfo itu. Juga, dengan alasan yang sama seperti dilontarkan Sofjan Wanandi. Mastel, bahkan mengirim surat resmi kepada Menkominfo, mempertanyakan aturan itu.
PT Excelcomindo Pratama (EP) yang tengah berancang-ancang memisahkan bisnis menaranya untuk kemudian dijual kepada pihak ketiga pun ikut-ikutan mempertanyakan aturan itu. Ada 7.000 menara yang akan dipisah dan dijual itu dan nilainya ditaksir sekitar Rp 7 triliun.
Dirut PT EP Hasnul Suhaimi mengatakan, persoalan bisnis menara itu bukan pada masalah teknis, melainkan soal permodalan. Kalau jumlah menara di Indonesia saat ini 50 ribu dan investasinya butuh Rp 1 miliar per menara, berarti dana yang dibenamkan di bisnis menara mencapai Rp 50 triliun.
“Dana sebesar itu, kalau bukan pemodal asing, siapa yang sanggup. Kalaupun bisa mungkin dari pinjaman bank,” kata Hasnul. Namun, apa yang bisa dilakukan Hasnul dan PT EP, kecuali comply alias manut saja terhadap setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah.
Asdep Telematika dan Utilitas Deputi V Menko Perekonomian Eddy Satriya merasa tidak pernah ada koordinasi soal perumusan aturan yang melarang asing masuk dalam bisnis menara. Seharusnya, untuk menutup sektor tertentu bagi asing terlebih dulu dikoordinasikan dengan kantor Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan dan pihak terkait, seperti BKPM dan tim Peningkatan Ekspor Peningkatan Investasi (PEPI) di Depdag.
“Selebihnya, tentu harus mendapat persetujuan dari presiden dengan cara membuat Perpres yang baru menggantikan Perpres No 111/2007,” kata Eddy Satriya.
Depkominfo yang dipimpin Muhammad Nuh sempat bungkam juga dihantam kiri-kanan, meski mereka tetap keukeuh pada pendiriannya. Apalagi ada dukungan dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang disampaikan Heru Sutadi, dan pengusaha nasional yang bergerak di bidang penyediaan menara, Dirut PT Solusindo Kreasi Pratama (Indonesian Tower) Wahyu Sakti Trenggono.
Depkominfo makin teguh ketika Kepala BKPM M Luthfi lantang bersuara dalam seminar bertajuk Prospek Menara Bersama bagi Pengembangan Industri Telekomunikasi Indonesia pada 17 April 2008. Didampingi Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar, Luthfi mengatakan, “Ini adalah kampung kita. Untuk bisnis menara, kita ingin dikerjakan sendiri oleh pengusaha dalam negeri. Ini komitmen kita bagi pengusaha nasional.”
Bersama Dirjen Postel Depkominfo, lanjut Luthfi, BKPM telah melaporkan masalah ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah itu, semua diam, meski hingga kini belum ada perubahan atas Perpres No 111/2007 itu.
BKPM dan Bapepam Bungkam Depkominfo di Indosat (2/habis)
Di penghujung 2008, Menkominfo Muhammad Nuh terhuyung. Ia angkat tangan, lalu angkat bicara. Dua bulan lebih ia bertahan dengan pendiriannya untuk menegakkan aturan. Ini berkaitan dengan keinginan Qatar Telecom (Qtel) mengakuisisi 65% saham PT Indosat Tbk.
Bukan maksud Menteri untuk membendung keinginan Qtel menguasai mayoritas saham Indosat, mantan rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) itu cuma ingin menegakkan aturan. Yakni, aturan yang dia abaikan ketika menerbitkan Peraturan Menkominfo No 2/2008 yang melarang asing masuk dalam bisnis menara. Itulah Perpres No 111/2007 tentang DNI.
Dalam kasus Qtel dan Indosat itu, Menkominfo keukeuh, investor asing, siapa pun dia, harus mengikuti aturan DNI. Yakni, untuk perusahaan telekomunikasi yang memiliki lisensi telepon tetap, investor asing hanya boleh menguasai maksimal 49% sahamnya, sedangkan untuk telepon selular boleh sampai 65%.
Indosat adalah perusahaan telekomunikasi yang memiliki lisensi paling lengkap. Mulai dari lisensi jaringan tetap, fixed wireless access (FWA), sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), sambungan langsung internasional (SLI), dan seluler hingga 3G dan 3,5G.
Oleh karena itu, sesuai Perpres No 111/2007 itu, Qtel tidak bisa mengakuisisi 65% saham Indosat. Kalau Qtel tetap ngotot dengan angka 65%, perusahaan telekomunikasi dari Qatar itu harus memisahkan lisensi jaringan tetap, yang terdiri atas StarOne (FWA), dan SLJJ.
“Peraturan yang mengharuskan pemisahan itu. Bunyinya 49% untuk jartap dan 65% untuk seluler,” ujar Menkominfo.
Persoalannya, seperti diungkapkan manajemen Indosat (Investor Daily, 12 November 2008), seluruh lisensi yang dimiliki Indosat itu sudah terintegrasi sedemikian rupa. Mulai dari jaringan cabang, karyawan, billing system, jaringan infrastruktur, hingga pengoperasian dan pemeliharaannya. Menara, misalnya, di situ ada radio pemancar (BTS) Mentari, IM3, dan StarOne.
“Meski sulit, pemisahan itu mungkin dan bisa saja dilakukan. Karena memang tidak ada yang tidak mungkin. Namun, bagaimana cost dan konsekuensinya belum bisa dikuantifikasi, karena sampai saat ini kami belum mendapat kepastian tentang juklaknya dari pemerintah,” kata Direktur Marketing Indosat Guntur S Siboro.
Rupanya, Qtel tak tinggal diam dengan kondisi itu. Apa gunanya mengakuisisi 65% saham Indosat kalau isi perut Indosat ternyata harus dhedhel-duel. Namun, Qtel juga tak mau kalau hanya menguasai 49% saham Indosat.
Depkominfo keukeuh pada pendiriannya untuk mematuhi aturan tentang DNI. Namun, Qtel terus berusaha untuk mengegolkan keinginannya menguasai 65% saham Indosat tanpa harus memisahkan bisnis StarOne dan SLJJ. Manajemen Indosat pun tampak tak rela, bila perusahaan yang sudah berusia 41 tahun itu harus dipisah-pisah.
Ketika pertama kali mengumumkan masuk mengambil 40,8% saham Indosat dari Singapore Technologies Telemedia (STT) pada medio Juli 2008, Ketua Qtel Grup Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani langsung mengumumkan jalinan hubungan strategis dengan Rachmat Gobel. Kala itu, Rachmat Gobel adalah presiden komisaris Panasonic Gobel, sekaligus sebagai wakil ketua Kadin Indonesia, yang juga dekat dengan kepala BKPM M Luthfi.
Tiba-tiba, pada 24 Desember 2008, ketua Qtel yang telah menjadi presiden komisaris Indosat itu mengeluarkan siaran pers yang isinya, pemerintah Indonesia telah memperbolehkan Qtel memiliki hingga 65% saham Indosat tanpa harus memisahkan unit usaha jaringan tetapnya.
“Ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan investor kepada sistem dan iklim usaha di Indonesia. Kami tidak meragukan bahwa hal ini akan membantu menarik lebih banyak investasi ke Indonesia, yang pada akhirnya akan menumbuhkan dan membawa manfaat untuk ekonomi dan bangsa Indonesia.” Demikian Sheikh Abdullah memuji keputusan pemerintah Indonesia itu.
Ada pertanyaan besar tentang persetujuan pemerintah Indonesia itu. Namun, jawaban datang dari Menkominfo, pas ketika jumpa pers Refleksi Akhir Tahun 2008 di Jakarta, pada 31 Desember 2008. Bahwa keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi dengan instansi lain, yang melibatkan Depkominfo, BKPM, dan Bapepam.
“Keputusan tanpa harus spin off itu merupakan hasil rapat antar departemen itu,” kata Nuh. Lalu, dia melanjutkan, "Kami sadar betul ada lembaga yang kewenangannya lebih tinggi dari Depkominfo soal investasi, ya... pada ujungnya terserah BKPM."
Nuh pasrah. Ia di-KO investor asing dalam kasus Qtel, setelah sebelumnya meng-KO investor asing dalam kasus menara. Skornya kini 1:1.