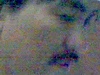"Pak Sus, Dina lulus ga?"
Yang ditanya mengangguk sehingga penanya memberondongnya dengan pertanyaan lain.
"Berapa NEM-nya?"
'Empat puluh enam koma lapan! Kalau anakmu, si Ucup, lulus juga? Berapa NEM-nya?"
"Lulus lah. 54,9!"
"Wah, hebat dong. Berarti rata-ratanya sembilan lebih!"
"Hebat apanya? Wong 60% jawaban soalnya sudah diisi."
"Iya sih! Dina juga cerita, waktu ujian, dia boleh bawa hp. Waktu ngerjain soal tiba-tiba ada SMS. Dia gak tau SMS dari siapa. Tapi isinya adalah jawaban soal ujian. Ha...ha..ha...."
Berdua tertawa. Pendengar lain ikut tertawa.
"Itu karena sekolah punya target agar semua siswanya lulus 100%. Demi nama baik sekolah dan demi nama baik guru-gurunya."
Inilah percakapan yang tersiar di warung kopi. Entah benar atau tidak, faktanya ada beberapa sekolah yang karena salah kasih bocoran jawaban akhirnya 100% siswanya tak lulus.
Apa yang sesungguhnya diharapkan dari program ujian nasional itu kalau sesungguhnya menjadi program penghancuran generasi muda Indonesia. Demi nama sekolah. Demi makin banyaknya siswa baru yang mendaftar. Demi kocek sekolah, saku yayasan dan pengurusnya. Ujung-ujungnya duit juga.
Ada yang hanya diam mendengar obrolan warung kopi itu. Ia ingin segera pulang menanyai anaknya.
"Tapi untuk apa?" Ia bergumam.
Nilai bagus atau jelek, ia juga tak kuasa. Ia tak ada kemampuan untuk melanjutkan sekolah anaknya ke perguruan tinggi.
Bagaimana mau ke perguruan tinggi kalau uang mukanya puluhan juta. Belum lagi uang SPP semesteran atau tahunan yang juga juta-jutaan.
"Aahh....!"
Ia teringat 27 tahun silam ketika ia lulus dari SMA di sebuah kampung di Sumatera Selatan dan mendapat undangan dari Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Andi Hakim Nasution. Orang tuanya senangnya bukan main karena cita-citanya dulu kesampaian juga, meski lewat anaknya.
Waktu itu, ayahnya sadar akan kemampuannya membiayai sekolah di perguruan tinggi, seperti keinginannya di era tahun 50-an. Kali ini, dengan tekad bulat, sang ayah mengirim juga anaknya ke Bogor. Untunglah tak ada uang pangkal. SPP-nya pun cuma Rp 22.500 per semester. Biaya hidup ketika itu cuma Rp 30.000 per bulan, termasuk uang kos-kosan.
"Berangkatlah kau anakku. Berangkatlah ke Bogor. Bapak akan usahakan biayanya."
Kini anak itu sudah menyandang gelar insinyur dan sudah bekerja di Jakarta. Dan, giliran insinyur itu yang mengurut dada memikirkan nasib anaknya yang baru saja lulus SMA.
"Gila. Bapakku dulu, hidup di kampung nun jauh di Sumatera Selatan bisa menyekolahkan enam anaknya hingga meraih sarjana semua. Di Jawa. Bapakku hanya lulusan SMP. Aku insinyur, tinggal di pinggiran Jakarta, kini aku bingung menyekolahkan anakku ke perguruan tinggi."
Ia merenung di depan TV sendirian.
"Dulu, orang desa dengan penghasilan pas-pasan bisa menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi. Kini, hanya orang kaya yang bisa meraih gelar sarjana. Edan!"
Sudah pukul 11 malam lewat. Lamunannya terjaga oleh iklan Mendiknas Bambang Soedibjo yang lantang bicara tentang biaya pendidikan SD gratis. SMP menyusul gratis.
"Aaahhh....! Apa sesungguhnya yang dilakukan pemerintah. SD dan SMP digratiskan, tapi menutup rapat orang tak mampu melanjutkan studi hingga ke perguruan tinggi, meski si anak memang pintar."
Ia mematikan TV dan 'mematikan' dirinya sendiri di tempat tidur. Tapi ia tetap tak bisa tidur juga hingga fajar menjelang.
Bogor, 22 Juni 2009
Monday, June 29, 2009
Subscribe to:
Comments (Atom)